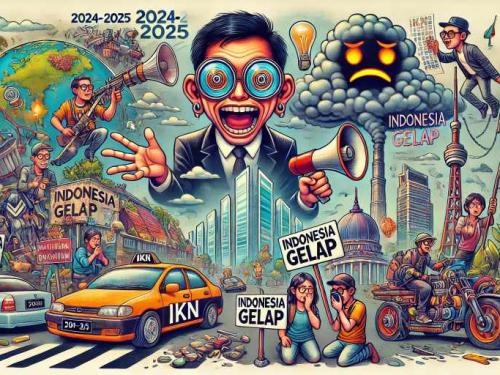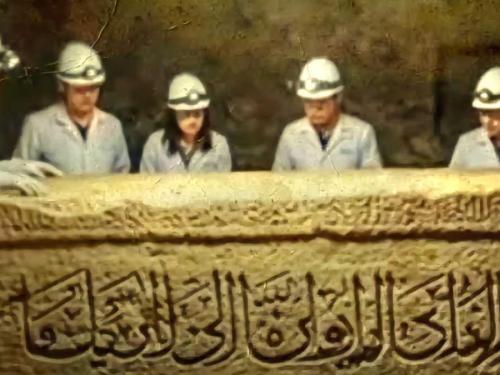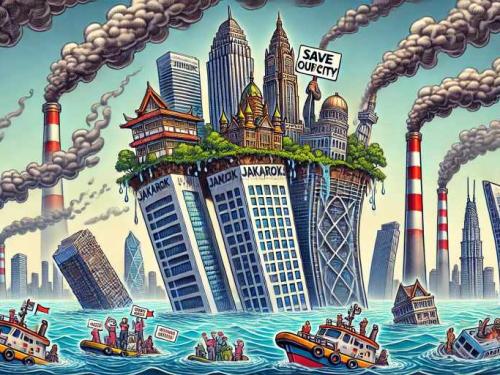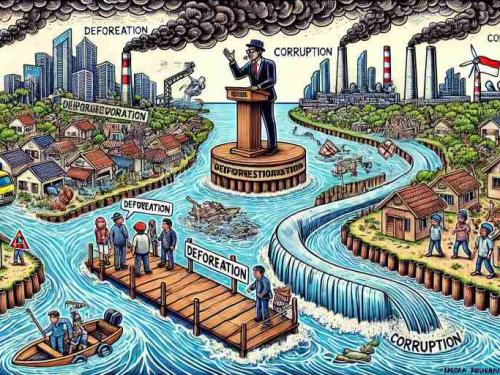Jakarta – Tahun 2025 menandai periode penuh gejolak dalam wajah hukum Indonesia. Sejumlah isu besar menyeruak dan membetot perhatian publik. Dari gedung-gedung pengadilan tinggi hingga forum-forum sipil, dari pasal-pasal hukum pidana hingga wacana supremasi militer, hukum menjadi arena konflik, kepentingan, dan pertarungan nilai. Dua hal paling mencolok mewarnai tahun ini: krisis integritas dalam lembaga penegak hukum, serta ancaman terhadap supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.
Di tengah arus informasi yang deras, deretan peristiwa hukum ini tidak hanya menjadi berita harian, tapi juga menggugah diskusi mendalam soal arah keadilan di negeri ini. Artikel ini mencoba memetakan isu-isu hukum paling trending sepanjang 2025, berdasarkan peristiwa aktual, sorotan publik, dan pendapat para ahli hukum.
Krisis Integritas Penegak Hukum: Benteng Keadilan yang Retak
Kejutan besar datang dari Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang menjadi garda konstitusi negara ini tercoreng skandal besar ketika Ketua MK terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap karena kasus suap. Pegawai Mahkamah Agung, advokat, panitera, dan hakim agung terjaring OTT oleh KPK. Tiga hakim ditahan atas dugaan menerima suap. Pegawai rutan KPK terlibat pungutan liar. Seorang polisi dipecat karena kasus pemerasan,” tulis Hukumonline.
Peristiwa-peristiwa ini mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. KPK yang dulu menjadi simbol harapan kini juga berada dalam pusaran sorotan, menyusul sejumlah isu internal dan dugaan praktik pelanggaran etik oleh pegawainya sendiri. Sementara itu, Mahkamah Agung, yang seharusnya menjadi puncak keadilan, justru harus berhadapan dengan dugaan keterlibatan hakim agung dalam pusaran suap kasus kasasi.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari melemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Reformasi peradilan yang telah digagas selama dua dekade terakhir tampak belum cukup membentengi institusi dari praktik koruptif yang sudah mengakar. Dalam diskusi publik yang digelar Lembaga Kajian Hukum dan Etika Publik, sejumlah pakar menyebut kondisi ini sebagai “krisis legitimasi” lembaga hukum, di mana kepercayaan rakyat terhadap integritas aparat hukum berada pada titik terendah.
Revisi UU TNI: Supremasi Sipil yang Mulai Tergeser
Jika krisis integritas adalah luka internal, maka revisi UU TNI adalah gejolak struktural yang menimbulkan ketegangan ideologis dalam bangunan hukum negara. Pada pertengahan 2025, DPR RI dan pemerintah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Salah satu poin revisi yang paling disorot adalah diperluasnya peran militer di ranah sipil—meliputi penempatan prajurit aktif di kementerian, lembaga negara, dan jabatan sipil strategis lainnya.
Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama kelompok pro-demokrasi dan akademisi. “Petisi online menolak revisi UU TNI ditandatangani oleh lebih dari 26.000 orang,” catat Wikipedia. Demonstrasi digelar serentak di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan mantan aktivis reformasi 1998 menyatakan kekhawatirannya bahwa revisi ini adalah bentuk kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap prinsip supremasi sipil yang telah dibangun pasca-Orde Baru.
Dalam diskusi yang digelar oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), pengamat militer dan hukum tata negara menegaskan bahwa perluasan fungsi militer di luar tugas tempur dapat menciptakan tumpang tindih wewenang serta membuka ruang pelanggaran HAM. Dikhawatirkan, militer akan mengintervensi kebijakan publik tanpa mekanisme akuntabilitas sipil yang memadai.
Pelanggaran Tender dan Praktik Bisnis Tidak Sehat
Sementara krisis integritas dan supremasi sipil menjadi headline, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berjuang di medan lain: bisnis curang. Tahun 2025, mayoritas perkara yang ditangani KPPU berkaitan dengan praktik kolusi dan pelanggaran tender.
“70 persen perkara yang ditangani didominasi oleh pelanggaran tender,” ungkap KPPU dalam laporan kinerjanya, dikutip Hukumonline. Praktik-praktik seperti penunjukan langsung fiktif, persekongkolan antar-perusahaan peserta tender, hingga manipulasi syarat teknis masih marak terjadi, bahkan di level pemerintah daerah.
Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghambat prinsip persaingan usaha yang sehat. Lebih jauh, pelanggaran tender seringkali menjadi pintu masuk praktik korupsi struktural yang melibatkan aparat, pengusaha, dan elite politik lokal. KPPU pun menekankan pentingnya penguatan sanksi dan kolaborasi dengan penegak hukum lainnya untuk menciptakan efek jera.
Kekerasan Seksual dan HAM: UU TPKS Belum Terimplementasi Maksimal
Isu kekerasan seksual tetap menjadi salah satu perhatian utama dalam ranah hukum dan HAM 2025. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan pada 2022, implementasinya masih menemui banyak hambatan.
Dalam Forum Bulaksumur Legal Outlook 2025 yang diselenggarakan Fakultas Hukum UGM, para pembicara menyampaikan keprihatinan atas lambannya aparat dalam menindaklanjuti laporan korban kekerasan seksual. “Kekerasan seksual sering kali tidak diprioritaskan dalam penyelesaian pelanggaran HAM,” kata seorang narasumber. Banyak kasus justru tidak sampai ke pengadilan karena aparat penegak hukum tidak memahami substansi UU TPKS atau terjebak dalam paradigma lama yang menyalahkan korban.
Di sisi lain, minimnya rumah aman, kurangnya tenaga pendamping hukum dan psikolog, serta budaya patriarkal yang kuat menjadikan korban enggan melapor. Aktivis perempuan menyuarakan perlunya pendidikan hukum yang progresif dan pendekatan berbasis keadilan restoratif untuk membela hak korban secara menyeluruh.
Konflik Agraria: Ketimpangan Perlindungan dan Pelanggaran HAM Struktural
Konflik agraria terus mewarnai dinamika hukum Indonesia, terutama di kawasan pedesaan, hutan adat, dan wilayah pesisir. Persoalan ini bukan hanya soal tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, melainkan mencakup penggusuran paksa, kriminalisasi petani, dan perampasan ruang hidup oleh korporasi besar.
Forum Bulaksumur juga menyoroti bahwa “masyarakat penggarap tanah menjadi rentan terhadap pelanggaran HAM akibat konflik agraria.” Pemerintah kerap berpihak pada korporasi besar dengan alasan investasi, tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis dari konflik yang timbul. Hukum, dalam banyak kasus, menjadi alat legalisasi ketidakadilan struktural.
Aliansi masyarakat adat, lembaga bantuan hukum, dan organisasi lingkungan mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan memperkuat Komnas HAM agar bisa bertindak lebih tegas dalam kasus agraria.
Bayang-Bayang KUHP Baru dan Ancaman terhadap Kebebasan Sipil
Tahun 2025 juga menjadi tahun transisi menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026. Meski belum berlaku, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menimbulkan keresahan publik.
Di antaranya adalah pasal tentang kriminalisasi hubungan di luar nikah dan larangan tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan, yang dipandang sebagai bentuk pengawasan moral oleh negara. Wikipedia mencatat bahwa pasal-pasal ini sejak awal mendapat penolakan dari aktivis HAM dan kelompok masyarakat sipil, karena dianggap bertentangan dengan prinsip privasi dan kebebasan individu.
Isu lainnya adalah pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru, yang membuka ruang bagi penerapan sanksi adat di luar kerangka hukum positif. Hal ini dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang tidak berada dalam komunitas adat dominan.
Hukum yang Dipertaruhkan
Di antara semua isu hukum trending 2025, satu hal menjadi benang merah: hukum Indonesia sedang dalam masa ujian berat. Krisis integritas yang mengguncang lembaga peradilan telah merusak kepercayaan publik. Di sisi lain, revisi regulasi yang memperluas peran militer dan mempersempit kebebasan sipil menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah demokrasi kita.
Hukum seharusnya menjadi fondasi keadilan, tetapi pada tahun ini, ia lebih sering menjadi arena pertarungan kuasa. Tantangannya bukan hanya memperbaiki institusi, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan tidak dikalahkan oleh kepentingan politik dan ekonomi.
Jika tahun 2025 adalah cermin, maka yang terpantul adalah wajah hukum yang masih compang-camping. Tapi di situlah juga harapan dimulai: dari kesadaran akan krisis, kita bisa mulai merajut ulang jalan menuju keadilan.
(*)