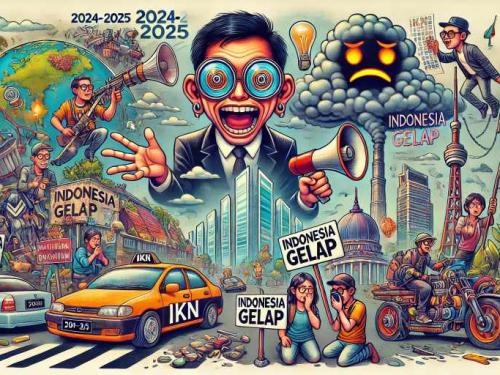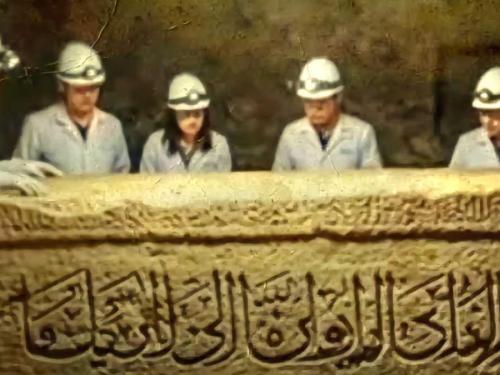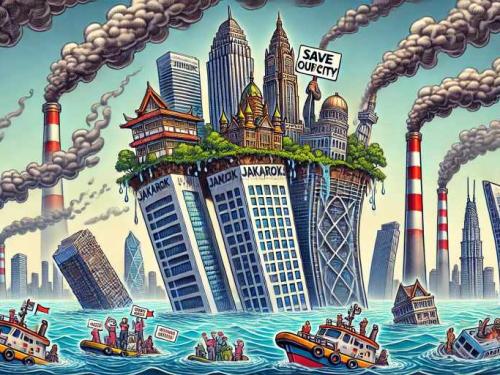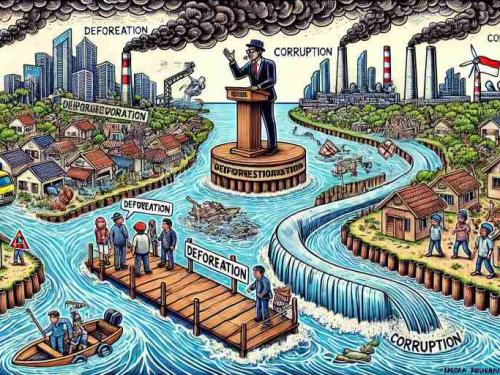Jakarta - Peredaran rokok ilegal di Indonesia pada tahun 2024 bukan sekadar isu ketertiban hukum, melainkan ancaman nyata terhadap pendapatan negara. Dengan potensi kerugian mencapai Rp97,81 triliun, fenomena ini menyerupai gunung es yang hanya tampak permukaannya. Di balik asap rokok tanpa cukai, tersembunyi persoalan yang jauh lebih kompleks—beririsan dengan kebijakan fiskal, perilaku konsumen, dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.
Menurut data dari Indodata Research Center, angka tersebut bukan hasil dari hitungan kasat mata, melainkan dari survei mendalam terhadap tren konsumsi dan distribusi rokok tanpa cukai yang dilakukan sepanjang tahun 2024. “Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp97,81 triliun,” demikian pernyataan mereka.
Jenis rokok ilegal yang paling mendominasi pasar adalah rokok polos, yaitu produk yang beredar tanpa pita cukai. Data menunjukkan bahwa rokok polos menyumbang 95,44% dari total peredaran rokok ilegal. Fakta ini diperkuat oleh hasil temuan Indodata yang mencatat bahwa “peredaran rokok ilegal didominasi rokok polos”.
Tidak hanya besar dalam nilai, tetapi peningkatan konsumsinya juga mencemaskan. Survei menunjukkan bahwa proporsi konsumen rokok ilegal meningkat drastis—dari kisaran 28% menjadi 46% hanya dalam kurun waktu satu tahun. Lonjakan ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi serta kenaikan tarif cukai justru mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif murah yang melanggar aturan.
Menghadapi situasi ini, negara tidak tinggal diam. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan telah melakukan penindakan terhadap 31.275 kasus perdagangan ilegal sepanjang 2024. “Nilai barang hasil penindakan mencapai Rp6,1 triliun dengan potensi kerugian negara sekitar Rp3,9 triliun,” ungkap Kementerian Keuangan. Angka ini mencerminkan kerja keras aparat Bea Cukai dalam mengawasi peredaran barang-barang ilegal, termasuk rokok tanpa cukai yang menyebar luas melalui jalur darat dan laut.
Namun, tantangan bagi Bea Cukai tidaklah kecil. Peredaran rokok ilegal kerap memanfaatkan celah distribusi di wilayah pelosok, kawasan perbatasan, dan bahkan lewat jalur digital yang sulit dijangkau pengawasan langsung. Selain itu, jaringan distribusi rokok ilegal kerap bergerak lincah, mengandalkan transportasi lokal, pengemasan ulang, hingga pemalsuan pita cukai untuk mengelabui aparat.
Akar permasalahan pun tak lepas dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kenaikan tarif cukai, meskipun bertujuan mengurangi konsumsi rokok, dinilai belum cukup efektif. Masyarakat yang tak sanggup membeli rokok legal akan cenderung beralih ke produk murah tanpa cukai. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa “kenaikan tarif cukai rokok mendorong perokok untuk mencari alternatif yang lebih murah, termasuk rokok ilegal”.
Pemerintah dihadapkan pada dilema: menjaga pendapatan negara melalui cukai sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok, tanpa menciptakan celah bagi peredaran ilegal. Tantangan ini membutuhkan pendekatan multidimensi—gabungan antara edukasi publik, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kapabilitas Bea Cukai di daerah, serta distribusi kebijakan fiskal yang lebih adil.
Sementara rokok ilegal masih mengalir di pasar-pasar tradisional dan pelosok negeri, kerugian negara pun terus menguap. Ini bukan sekadar soal angka triliunan, melainkan soal keberlanjutan sistem fiskal dan kepercayaan publik terhadap negara dalam mengelola sumber dayanya. Selama regulasi, pengawasan, dan edukasi belum berjalan seiring, tampaknya asap rokok ilegal masih akan terus mengepul—membebani negara, diam-diam. ***